"Aku suka langit."
Itulah alasan yang kulontarkan kala bocah setiap kali orang tuaku menegur hobiku berbaring di lapangan tenis sebelah rumah. Saat itu pohon cheri masih tumbuh di sudut kanan dekat bangku pemain, mendayu akibat desiran angin serta tawa bocah yang berebut rubi masak yang menggantung menggoda.
Setiap sore, ayahku adalah salah satu dari kumpulan petenis regional kampung yang unjuk bakat dalam meregangkan otot-ototnya. Kami bocah-bocah ingusan hanya menunggu, kalau tidak memungut bola atau bermain ular naga. Tapi aku tidak.
Dengan perasaan awas akan terhantam smash, aku duduk di kursi tinggi milik wasit sambil menengadah, menerawang awan yang meluncur dalam infinitas magenta. Senja menggelayut, menanungi impian-impianku. Pesawat terbang, E.T. yang menginvasi, serta sapaan naga-naga yang melindungi bumi; semua terarak dalam lamunan tinggi, di atas mega-mega.

Dan kesenanganku berlanjut tidak hanya kala sore namun pagi, siang, hingga ketika kebetulan menyebrangi lapangan saat malam. Menghamparkan diri di dekat pohon ceri, kemudian mengetuk gerbang khayal yang menjalin layaknya jembatan angan-angan. Rasanya menyenangkan sekali melupakan keberadaanmu menuju dunia yang bahkan tak perlu memperhitungkan satuan nafas. Merangkai sebuah masa depan.
Dua setengah tahun rutinitas itu melengkapi daftar kewajibanku (disertai menangkap kucing dalam selokan samping tempatku biasa berbaring) telah usai, kini aku terlalu sibuk memikirkan pekerjaan fanaku yang menumpuk. Lapangan kini mulai mengusap wajah; lahan parkir dengan badak besi berjajar yang merenggut masa muda kami, serta pengecoran beton tiap sudut yang merobohkan pohon kelahiran kami. Semua berdifusi dalam rangkaian materialisasi dan realisasi yang biasa kau sebut pendewasaan.
Namun siapa yang peduli jika sekelilingmu adalah deadline dan formalitas adalah yang kau junjung tinggi. Tombak yang menghujung kepada memori terliarmu untuk menjadi raksasa, merajai masa depan yang kau susun sendiri. Berkali-kali kau menengadah dengan angkuh, namun asa kini hanya gurauan; semua takluk pada kejamnya lidah dunia. Membelenggu, bertahun-tahun hingga peluh darah kini menghitam.
Dengan gontai aku melangkah maju menuju tanah tempatku mengubur fantasi. Tepat sepuluh hingga lima belas senti di bawah beton dingin inilah, ranjang tanah, semua probabilitas bernilai satu, inversi sebuah fungsi adalah reversibel. Apa yang mungkin adalah iya, begitu sebaliknya.
Kurebahkan diriku di samping makam pohon kehidupan (kini berganti menjadi sedan hitam), hingga kilatan oranye cakrawala membayang mengaburkan komplikasi nyata. Kenyataan, dimana mimpi adalah apa yang kau rangkai namun ekspektasi adalah yang kau hadapi. Lebih buruk, dirimu bukanlah individu yang berkuasa namun ribuan semut rapuh dan mudah pecah begitu saja. Pendewasaan adalah prioritas nilai serta norma yang mencekik, bukan peri musim semi dengan sayap terbang sedikit menukik.
Kukira mimpi memang abadi, dan semua orang berhak menjadi anak kecil untuk sesaat. Menggali jati diri yang terkubur dalam kemunafikkan realitas yang menjengkelkan, seperti kenangan kecil kami yang polos di bawah kejamnya beton tak bersyarat ini.
Dan kesenanganku berlanjut tidak hanya kala sore namun pagi, siang, hingga ketika kebetulan menyebrangi lapangan saat malam. Menghamparkan diri di dekat pohon ceri, kemudian mengetuk gerbang khayal yang menjalin layaknya jembatan angan-angan. Rasanya menyenangkan sekali melupakan keberadaanmu menuju dunia yang bahkan tak perlu memperhitungkan satuan nafas. Merangkai sebuah masa depan.
Dua setengah tahun rutinitas itu melengkapi daftar kewajibanku (disertai menangkap kucing dalam selokan samping tempatku biasa berbaring) telah usai, kini aku terlalu sibuk memikirkan pekerjaan fanaku yang menumpuk. Lapangan kini mulai mengusap wajah; lahan parkir dengan badak besi berjajar yang merenggut masa muda kami, serta pengecoran beton tiap sudut yang merobohkan pohon kelahiran kami. Semua berdifusi dalam rangkaian materialisasi dan realisasi yang biasa kau sebut pendewasaan.
Namun siapa yang peduli jika sekelilingmu adalah deadline dan formalitas adalah yang kau junjung tinggi. Tombak yang menghujung kepada memori terliarmu untuk menjadi raksasa, merajai masa depan yang kau susun sendiri. Berkali-kali kau menengadah dengan angkuh, namun asa kini hanya gurauan; semua takluk pada kejamnya lidah dunia. Membelenggu, bertahun-tahun hingga peluh darah kini menghitam.
Dengan gontai aku melangkah maju menuju tanah tempatku mengubur fantasi. Tepat sepuluh hingga lima belas senti di bawah beton dingin inilah, ranjang tanah, semua probabilitas bernilai satu, inversi sebuah fungsi adalah reversibel. Apa yang mungkin adalah iya, begitu sebaliknya.
Kurebahkan diriku di samping makam pohon kehidupan (kini berganti menjadi sedan hitam), hingga kilatan oranye cakrawala membayang mengaburkan komplikasi nyata. Kenyataan, dimana mimpi adalah apa yang kau rangkai namun ekspektasi adalah yang kau hadapi. Lebih buruk, dirimu bukanlah individu yang berkuasa namun ribuan semut rapuh dan mudah pecah begitu saja. Pendewasaan adalah prioritas nilai serta norma yang mencekik, bukan peri musim semi dengan sayap terbang sedikit menukik.
Kukira mimpi memang abadi, dan semua orang berhak menjadi anak kecil untuk sesaat. Menggali jati diri yang terkubur dalam kemunafikkan realitas yang menjengkelkan, seperti kenangan kecil kami yang polos di bawah kejamnya beton tak bersyarat ini.
Malang, 10 Juni 2013





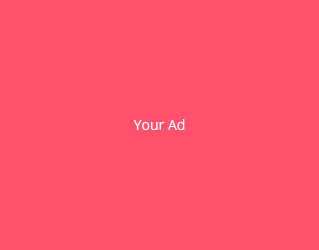

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih telah berkunjung. Sila untuk bertandang kembali bilamana saya membalas :)