Walau ini semua tampaknya konyol, tetapi ada satu mimpi yang membuat saya terjebak dalam faham mimpi bukanlah sekedar proyeksi bawah sadar. Bahkan aku tak yakin apakah ini mimpi, ataukah teriakan roh yang tersesat dalam perjalananya.
Hari yang panas. Matahari tengah hari menusuk mataku tanpa ampun, menyusup melalui kaca mobil yang hanya dibuka setengah. Tubuh kecilku yang dibalut seragam TK berwarna biru-putih meronta, memaksa ibuku membukakan jendela untukku. Sayup-sayup aku mendengar 'Tidak, jangan.' Kemudian semuanya menjadi sunyi. Ibuku hanya tersenyum sambil bilang 'Habis ini kita sampai kok.'
'Kemana?' tanyaku. Aku melihat jalanan semakin menyempit, menyisakan hutan bambu dengan sungai berwarna kuning di sebelah kananku dan rumah-rumah tua yang terbengkalai di sisi kiri jalan.
Aku lupa apakah ibuku sempat menjawab atau tidak, tetapi yang jelas tiba-tiba cuaca menjadi sangat mendung. Jalanan depanku menjadi sangat gelap, namun bukan berarti hitam. Kelam. Ya, kelam adalah kata yang tepat. Tiba-tiba jalanan berakhir dan ibuku mematikan mesin mobil. Ia membukakan pintu untukku dan menarikku keluar.
'Kita sudah sampai.'
Aku mencoba mencerna apa yang ada di depanku dengan otak usia 5 tahunku. Sebuah gerbang raksasa, dengan pilar-pilar menjulang mirip dengan yang kau lihat sebagai ikon Disneyland di setiap film-film. Mirip, namun bedanya semua di depanku berwarna kelabu. Pilar-pilar tersebut disatukan oleh sebuah gerbang berbentuk jeruji besi yang tertutup rapat dan sekali lagi, berwarna kelabu.
Ibuku mengajakku masuk, tetapi seingatku loket penjual tiket sudah tutup. Tidak ada siapa-siapa. Bahkan angin pun tidak berhembus, matahari tidak berani menampakkan keagungannya. Senyap.
Tetapi entah tertarik dengan apa, aku mendekati jeruji besi itu dan melihat ke dalam. Sunyi, kelabu, berdebu. Tetapi tiba-tiba beberapa detik kemudian aku melihat sebuah kolam renang yang cukup besar, air-air mancur ditembakkan di sana sini. Semuanya kini berwarna. Naun yang paling aku ingat sampai sekarang: satu atau dua badut raksasa, mengenakan topeng yang cukup mengerikan dengan senyum yang paling tidak kusukai, melambaikan tangan padaku berusaha mengajakku masuk.
Aku sudah lupa akan keberadaan ibuku yang tiba-tiba saja berhenti berperan dalam panggung mimpiku. Aku berusaha membuka pintu, yang anehnya tidak terkunci, terbuka dengan mudahnya dan masuk ke dalam. Badut-badut tadi (masih dengan topeng senyum yang sangat kubenci) tetap melambaikan tangan menyambutku. Namun ketika aku berjalan ke arah mereka, semuanya tiba-tiba hilang.
Semuanya meninggalkanku. Aku sendirian di tempat itu, menangis, hingga aku terbangun.
Hilang. Kelabu. Sunyi. Senyap.
Mimpi itu mungkin terdengar seperti mimpi-mimpi buruk biasanya yang lain, tetapi mimpi itu muncul lebih dari sekali. Anehnya mimpi inilah yang sampai sekarang belum pernah dan belum bisa aku lupakan. Dan sekitar akhir kelas 3 SMP ketika aku diperbolehkan mengendarai sepeda motor, aku memutuskan untuk pergi ke rumah temanku di salah satu sudut terpencil di kotaku.
Tiba-tiba aku melalui sebuah jalan yang mirip dengan mimpiku.
Bukan mirip, tetapi itulah jalan yang aku lalui dulu!
Sepulang dari rumah temanku, aku menyusuri jalan itu. Jalan yang sama, dengan rimbunan pepohonan di kanan jalan, sungai yang mengalir berwarna cokelat, dan rumah-rumah tua di sisi kiri jalan. Begitu rimbunnya pepohonan di sepanjang jalan hingga matahari tampak tak berdaya, menyisihkan bayang-bayang redup.
Dan jalanan itu berujung.
Aku memacu dengan cepat sepedaku, tak sabar walau kerikil menghalangi.
Dan saat itulah aku berhenti menarik gas, sedikit kecewa.
Tak ada apapun selain lapangan kosong di ujung jalan tersebut. Bahkan bukan lapangan, tetapi hanya tanah kosong yang bahkan tidak cukup luas untuk dijadikan sebuah rumah.
Dan tak ada secicit burung pun, alunan manja angin, yang rela menemaniku di tengah kekecewaan dan rasa penasaran yang mengalir sendu di bawah sadarku.





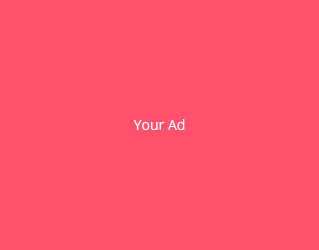

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih telah berkunjung. Sila untuk bertandang kembali bilamana saya membalas :)