“Assalamualaikum,” kataku menendang-nendang irama. Jantungku
meronta keluar dari biliknya. Ia tahu cepat atau lambat aku akan mengalami
gagal jantung, ah, atau gagal move on?
Siapa sih yang tidak mau bertemu dengan orang – atau
bajingan – yang lama tidak kau temui – atau berusaha menjauh darimu – dan
dengan sukarela yang Arjuna pun menjadi kera karenanya ia mengajakmu untuk
menelponnya. “Nomer teleponnya si X berapa?” adalah pesan pertama dan
terakhirnya yang mampir ke ponsel. Namun Otak yang hobi ngasih wejangan sudah
berjongkok putus asa karena si Hati yang egosentris menendang selangkangannya
dengan pernyataan “Last chance or never, oi!” dan sensor motorik pun
manggut-manggut saja sehingga di sinilah aku, bercinta dengan kotak telepon tua
angker yang mungkin genderuwonya saja sudah pindah digerus kapitalisme.
Dan masih berfungsi.
Tidak dapat dipungkiri, aku benar-benar deg-deg an menunggu
setiap “nuut” diganti dengan “Halo”. Sejuta skenario mekar sebagai spektrum
imajinasi di insting terliarku. Ketika waktu yang dinanti-nanti pun tiba,
sebuah suara maskulin nge-bass dari
ujung sana seakan mengedipkan mata kepadaku, membuat aortaku bocor dengan
endorfin jenuh. Aku pun reflek jungkir
balik campur Harlem Shake dan
segera terbata-bata berusaha memuntahkan sejumput kalimat, yang anehnya, tak
kunjung bicara. Aku merasa budeg –
tuli – bahkan tawa gesekan daun yang lagi ajep-ajep
sedari tadi kini tak terdengar digantikan oleh sejuta amplitudo dari
suaranya yang seakan mengetuk pintu kesadaranku. Karena suara itu begitu jelas,
begitu terdengar, dari balik ikat rambutku dan nafasnya yang bau peppermint menusuk indra perasaku dan aku tak pernah salah!
Ketika kutoleh di belakang, ku lihat dia memegang handphone Nokia 5760-nya yang ketinggalan jaman sambil
menggelengkan kepala. Tanpa bantuan verbal pun aku bisa melihat dia melontarkan
pertanyaan “Ngapain kamu disini?” dan kulempar kembali pertanyaan itu. “Kos-ku
deket sini, tahu.” Jawabnya. Aku melihat kembali matanya yang penuh dengan rasa
rindu – atau itu refleksi dari diriku? – dan segera kudekati dirinya. Sambil
menahan nafsu untuk memeluknya, aku meneteskan air mata, menunduk. Ia segera
menatapku penuh tanya. “Ngapain nangis?” “Kangen, tahu.” Wajahku merah padam
kayak tomat yang baru direbus, dia tertawa sambil minta maaf kalau dia selama
ini tidak pernah mengontakku lagi.
Kali ini kuberanikan melihat matanya,
cokelat penuh kehangatan seperti Rotiboy yang baru keluar dari oven, mengembang
dengan harapan dan senyum itu – senyum yang sama saat dia nyatakan ‘aku sayang
kamu’ dan juga saat ‘maaf ya kita harus berakhir di sini’ – senyum yang bikin
gila! Aku harus menelan ribuan air liur dulu sampai syarafku sadar dari
mabuknya dan aku berniat untuk menggenggam tangannya. Dia mengulurkan tangannya
duluan! Dengan liberalisme jiwa dan raga sontak aku menggenggamnya,
Dan tiada!
Ia ada, tapi tiada!
Bajul,pikirku.
Dimana kamu! Aku berusaha menggenggamnya, tapi melorot terus. Aku mulai meleleh
dalam kristal air mata. Dia sekali lagi tersenyum, dan dengan tertawa sinis
penuh kemenangan Otak pun twerking sambil
mulai memutar bioskop drive thru masa-masa
kelam beberapa saat setelah putus. Lho jangan lari! Jangan! JANGAN!
Ending-nya simpel,
cuma serangan jantung mini, di kotak telepon di tempat yang sama dan gagang
telepon menempel di telingaku sambil bernyanyi “Maaf, nomor yang anda tuju
tidak dapat dihubungi.”






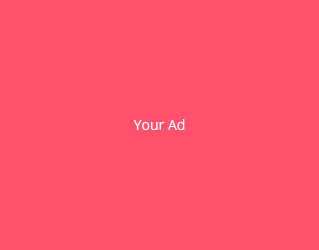

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih telah berkunjung. Sila untuk bertandang kembali bilamana saya membalas :)