 |
| Oleh Adityo Wahyu Wicaksono. 22 Agustus 2015. Loose leaf B5, pensil mekanik. |
Ship.
Aku cemburu pada ikan duyung itu.
Pertama kali aku bertemu dengan lelaki itu ketika ia duduk termenung di ujung dermaga. Aku mendekatinya dengan perlahan dan ia membalasnya dengan sapaan yang ramah. Ia tampak setahun lebih muda dariku. “Ada sesuatu yang misterius di dalam laut,” ujarnya ketika aku menanyakan alasannya kemari. Aku menyebutkan namaku. Aku menyebutkan pula tempat tinggalku. Aku juga menjelaskan betapa aku juga mencintai lautan dan rutin mengunjungi dermaga ini untuk memandang matahari yang tengah beristirahat. Ia hanya tersenyum dan diam. Ia tak menyebutkan nama maupun asalnya. Tapi itu tidak penting karena aku tahu aku telah jatuh cinta padanya seperti aku terobsesi hamparan biru asin itu.
Aku cemburu pada ikan duyung itu.
Hari berganti, namun sore tetap sama. Sebuah teh dan kopi, angin darat yang mulai menggelitik deburan pasir berwarna merah muda, serta diam. Kami berdua sepakat bahwa diam adalah cara kami menghargai Semesta, lebih-lebih Laut. Kami membiarkan diri kami dimanja oleh percikan tirta yang tak jemu-jemunya menggoda. Lelaki itu selalu memejamkan mata kala kami berdua mencelupkan betis kami menembus permukaan air bersuhu hangat. Lelaki itu tahu Semesta tengah mencintainya dan begitu pula perasaannya hampir tak dapat dibendung untuk mencumbu Semesta, menjadikannya sebagian milik pribadi, egois, hampir seperti balita menyusu pada tubuh ibunya.
Dan aku tahu Semesta tengah mencintaiku yang hadir dalam bentuk lelaki itu.
Aku cemburu pada ikan duyung itu.
Itulah kata pertama yang ia lontarkan setelah dua puluh lima menit perjalanan dengan kapal feri kecil milik kakekku menuju tengah selat; diapit dua daratan masif yang berpendar kala malam dan asap metropolitan yang menyesatkan siapapun yang tergoda oleh kekayaan. Angin darat dini hari yang menusuk tidak menggoyahkan tubuhnya yang membara dilanda kekagumannya terhadap pantulan purnama pada cermin raksasa yang seolah tak berujung. Ia bergegas keluar dari ruang kemudi dan menggelar tikar di dekat pagar pembatas. Dengan isyarat ia mengajakku duduk di sampingnya sambil menyeruput cokelat hangat dan memandang kubah angkasa.
“Ikan duyung?”
“Ya, ikan duyung itu. Selalu tiba saat purnama. Aku cemburu padanya. Ia mencintai laut dan laut berbaik hati untuk membiarkannya hidup di dalamnya.”
“Kau pernah bertemu dengannya?”
“Tentu saja. Kami berkenalan musim lalu, namun setelahnya aku selalu mencium kening dan lehernya dan punggungnya yang terbuka dan kami bercinta semalaman di bawah naungan debu ekstraterestrial.”
“Seperti sekarang ini?”
“Seperti yang akan kulakukan setelah ini.”
Wajahnya datar; ombak di wajahnya begitu tenang seperti deburannya di bawah kapal kami.
Namun tsunami menghantam pipi dan dada kiriku.
Aku cemburu pada ikan duyung brengsek itu.
Namun selalu kudapati diriku menemani lelaki itu tiap purnama menetas; ia akan turun dengan baju ala kadarnya menuju lautan yang sunyi, melabuhkan diri dan cintanya pada ikan duyung hingga pasang tertinggi tiba. Ia melompat – BYUR – dan menghilang ditelan remang awan dan lika-liku terumbu karang. Aku mendengar desahannya yang disampaikan oleh gemuruh laut yang bersimpati. Tak pernah sekalipun aku melihat ikan duyung itu, tetapi lelaki itu selalu kembali ke dek kapal sambil basah kuyup dengan nafas memburu seolah telah melepaskan segala gairahnya serta senyum kepuasan yang kau biasa temui pada insting purba alpha male.
Ia mendekat padaku dan menyentuh lembut pipiku.
“Terima kasih selalu membantuku untuk menemuinya.”
Lalu ia akan bercerita panjang lebar mengenai Venus nautikal itu; lekuk tubuhnya, tiga warna di iris matanya memantulkan tumpukan ganggang tempatnya bersembunyi, gemerlap sisik ekornya, rambutnya yang berwarna oranye muda ditimpa sentuhan chandra. Ia memimikkan suaranya; bening, datar, namun sebuah feromon mistis menggoda di dalamnya.
“Apakah kau masih mencintai laut? Seperti aku mencintai ikan duyung itu?” tanyanya tiba-tiba.
Seperti aku mencintaimu, Bangsat, namun aku terdiam menikmati aroma amis di celah lehernya yang membayang dan perlahan memabukkan.
Aku cemburu pada ikan duyung dan lelaki brengsek itu.
Hatiku telah melacurkan dirinya hanya untuk memenuhi kebutuhan primer akan sentuhan dari lelaki itu. Namun kali ini ia, yang kehilangan keperawanannya pertama kali saat aku jatuh cinta, mulai menagih bayaran.
Kesabaran.
Hanya malam purnama seperti yang lain. Air pasang mulai menunjukkan eksistensinya dan gelombang konveksi kehangatan yang tersimpan dalam gelanggang marina menerpa kapal kami. Lelaki itu mengenakan pakaian abu-abu dan celana pendek – seperti biasanya – dan mulai berjalan ke arah dek ketika ia tiba-tiba berhenti dan memutar tubuhnya ke arahku,
“Kurasa sudah saatnya.”
Aku terdiam dan memasukkan tanganku ke kedua saku jaketku. Seperti malam purnama yang lain, aku mengenakan piyama panjang dan jaket parka dengan berbagai saku terpasang.
“Aku hendak meninggalkan daratan untuk meminang ikan duyung itu.”
Seperti malam purnama yang lain, ia selalu meyatakan itu.
“Tidak, Liebe, kau tidak akan melakukan itu.”
Seperti malam purnama yang lain, suaraku selalu bergetar dan berharap ia akan mengangkat bahu, tertawa tipis, “Yah itu tidak mungkin, kau benar”, sebelum akhirnya melompat turun ke laut dan memanjat tangga kembali ke dek. Seperti malam purnama yang lain.
“Aku yakin kali ini. Aku akan meminangnya, kami berdua akan menjadi penghuni laut yang paling romantis karena kecintaan kami pada samudera! Katakan pada langit aku akan merindukannya, Sayang, karena aku akan meninggalkannya untuk selamanya, menggantikannya dengan rangkaian Portuguese Man ‘o War atau Mola-mola yang membayang di antara permukaan! Katakan pada tanah aku berterimakasih, karena lubuk laut akan menjadi saksi derap langkahku dan palung akan menjadi rahasiaku. Katakan, Sayang, katakan, bahwa aku akan menikahi ikan duyung yang paling kucinta, o Semesta terberkatilah diriku, katakan...
“Katakan pada dirimu, terima kasih telah menjadi kawan yang setia.”
Tidak seperti malam yang purnama yang lain, sebuah bunyi yang memekakkan telinga membelah seperempat malam dan menghunus jauh menembus horizon.
Sebuah peluru berkaliber tiga puluh sentimeter menembus dahi kirinya. Ia terjerembab ke belakang dan merintih kesakitan. Ia mengumpat. Aku menendang kepala dan menghancurkan seperempat tengkoraknya dengan injakan.
“Kau ingin tinggal di laut?!” Aku berteriak, menghabiskan segala dendam yang menyumbat paru-paruku layaknya flek. Nafas lelaki itu memburu, namun kakiku tetap menindih kepalanya. Aku mengeluarkan pisau dapur yang sangat tipis sehingga cocok untuk menyayat dari saku kananku dan mulai mengiris bagian bawah lutut kanannya.
“Akan kupenuhi.”
Sekitar tiga belas menit sesudahnya, aku melempar jasadnya ke laut dan membawa pulang sebuah kantong plastik agak besar dan apapun isinya, telah kupotong kecil-kecil hingga tak ada seorang pun di rumah yang curiga ketika sarapan disajikan di meja.
Aku tidak lagi cemburu pada ikan duyung itu.
Saat aku beranjak dewasa, aku meninggalkan pantai dan mencari pekerjaan yang menjanjikan di kota. Tidak ada seorang pun yang mencurigaiku malam itu, toh juga aku tak peduli. Aku sanggup mengubur dinginnya malam, menepis basahnya laut, dan juga menghalangi cahaya rembulan yang menjadi saksi kala itu. Kenangan akan masa itu tidak menggangguku namun selalu abadi, tiada tergerus waktu layaknya mitos mengenai ikan hiu raksasa yang ditemukan nelayan di tengah lautan tanpa ekor dengan kepala setengah hancur dan lubang di pelipis kiri. Para penduduk sekitar tak tahu bagaimana ia mendapat luka itu, para ilmuwan pun tak menemukan tanda-tanda ia diserang.
Hanya satu orang yang tahu. Satu orang yang begitu mencintai lautan.





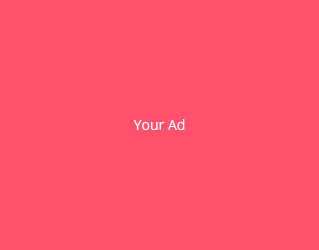

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih telah berkunjung. Sila untuk bertandang kembali bilamana saya membalas :)