Saya memutuskan pulang tanpa menghabiskan pencuci mulut malam itu. Setelah membayar sewa parkir, saya melesat membelah malam yang tak kalah cerahnya dari siang hari karena gemerlap lampu cafetaria dimana-mana. Malam itu malam Minggu dan jalanan yang saya lewati adalah Silk Road-nya Malang: muda-mudi memenuhi jalanan untuk mencari lahan parkir dan saya termasuk pengendara yang hanya bisa merayap menanti mereka menepi agar jalanan lengang. Jalanan ini merupakan tujuan pertama seorang pria ketika wanitanya bilang “Terserah mau makan dimana” karena dijamin mereka bisa berhenti di salah satu sisi karena cafetaria layaknya ruko sepanjang jalan ini, Jalan Soekarno-Hatta.
Kota Malang memang tidak dapat dipungkiri kini merupakan salah satu ‘Ibukota Cafetaria’ yang terjangkau bagi para mahasiswa maupun pelajar sekolah. Sebelumnya, masyarakat mengenal ‘Cafetaria’ sebagai tempat minum kopi yang dikelola secara franchise sehingga harganya cukup mahal. Tidak banyak usaha cafetaria yang bertempat di pinggir jalan apalagi rumah sendiri dan lebih memilih menyewa stan di mal sehingga membatasi pelanggan yang berasal dari kalangan bisnis saja. Selain cafetaria, masyarakat Kota Malang mengenal juga eatery seperti bistro steak yang legendaris dengan harga yang dapat ditebus oleh pejabat ataupun bila sedang ada acara keluarga. Tidak memiliki budget untuk kedua jenis di atas tetapi ingin makan ‘mewah’? Maka pilihan dijatuhkan pada restoran cepat saji. Setidaknya itulah jenis rumah makan yang diketahui oleh masyarakat di lingkungan tempat saya tinggal sebelum akhirnya Racel Risol muncul menembus batas definisi dan tradisi.
Racel Risol bukan cafetaria yang saya datangi pertama kali. Lai-Lai’s Illy Cafe saya kunjungi secara tak sengaja dan menemukan bahwa menu yang disajikan memang enak tetapi belum terjangkau oleh kantung pelajar (saat itu SMA) sehingga ketika seorang teman menjelaskan bahwa ada cafetaria yang cozy dengan menu berkisar antara Rp5000-Rp15000, saya langsung menyetujuinya. Dia benar; Racel Risol yang dibangun dengan memanfaatkan garasi dan halaman depan sebuah rumah di kompleks kecil menghadirkan suasana homey dan comfy dengan harga yang ramah di kantong. Saya masih ingat pesanan pertama saya: risol jagung-mayonaise yang disajikan dengan tomat dan selada di atas talenan serta segelas frape-frape atau es kopi yang di-blend dengan biskuit oreo. Semuanya dapat ditebus dengan Rp15000 saja.
Selama kurun waktu dua tahun saja gaya hidup baru ini merubah wajah kota Malang. Cafetaria mulai dibangun dimana-mana dengan beragam konsep dan harga yang berbeda. Baegopa, eatery berbentuk satu rumah penuh berlokasi tidak jauh dari Racel Risol muncul dengan menu khasnya yaitu olahan ayam yang disajikan sedemikian rupa sehingga mampu membekas di hati pelanggannya. Karena berkonsep rumah makan, Baegopa juga mampu mendobrak usaha kuliner yang ditujukan untuk kaum muda yang belum kenyang bila menyantap makanan cafetaria yang pada umumnya berporsi kecil. Lain halnya dengan BVGIL Gelato & Friends yang menawarkan menu seputar es krim gelato untuk disantap di halaman cafe yang terbuka.
Sisanya silahkan Anda kunjungi sendiri puluhan cafetaria yang terpencar di seluruh penjuru kota Malang. Terdapat akun media sosial yang mendedikasikan dirinya untuk mengantarkan makanan di layar ponsel Anda, sehingga Anda akan terbantu untuk mencari cafe mana yang cocok sesuai selera, dompet, bahkan mood.
Di tengah persaingan sengit tersebut saya menyadari hilangnya satu hal yang menurut saya penting: keramahan. Bukan, saya bukan membahas ramahnya pelayanan di cafe. Keramahan yang saya maksud adalah suasana hangat yang ditawarkan sebuah cafe kepada para pelanggannya; bagaimana sebuah cafe menerima segala pelanggan dan berperan sebagai rumah kedua bagi mereka. Keramahan yang menyambut pelanggan agar tetap tinggal di cafe karena cafe itu sendiri dan bukan karena wifi gratis berkecepatan tinggi. Keramahan yang mengajak pelanggannya untuk menemukan rasa nyaman dan menjadikan salah satu masakan dalam menu sebagai makanan favoritnya. Keramahan yang membekas di hati pelanggan untuk selalu kembali ke sana karena rindu.
Datang, makan, bayar, lalu pulang. Itulah kesan yang saya rasakan ketika mengunjungi cafetaria ‘newbie’ yang muncul belakangan ini. Meskipun konsep yang ditawarkan berbeda, tetapi tidak ada kesan yang mengajak saya untuk kembali lagi. Promosi yang ditawarkan di sana-sini tampak hanya seperti diskon makan musiman. Even-even yang diadakan oleh cafetaria baru pun monoton: selfie lalu gratis makan x, asal follow y, z, a, b, c.... YA! Monoton menjadi kosakata yang terngiang dalam benak saya karena setiap cafe berlomba-lomba menjadi yang terbaik, bukan dirinya sendiri. Saya kecewa ketika Amsterdam – salah satu bistro terkenal di Malang yang hanya didatangi ketika ada tamu penting atau acara keluarga saja – menyulam tampilannya menjadi cafe ‘bersahabat’ dan ‘terjangkau’. Harga yang ditawarkan memang lebih murah dibandingkan sebelumnya, tetapi Amsterdam kini kehilangan nama baiknya; seolah pejabat kerah putih yang memiliki pelanggan setia kini merangkak bersama bocah SMP demi mengejar kuantitas. Konsep yang ditawarkan pun rupanya tidak jauh berbeda dengan cafe newbie lain yang nyaris melupakan perannya sebagai rumah kedua para pelanggan.
Belum habis pikiran saya terhadap perubahan yang mencengangkan, Racel Risol ikut merombak rupa fisiknya menjadi rangka beton dan lampu pijar di setiap meja. Pertama kali saya tiba di wajah yang baru, apa yang saya sebut welcoming warmth menguap tergantikan dinginnya tembok dan pilar yang secara tak langsung menjadi sekat antar pelanggan. Menu yang ditawarkan pun mulai tampak monoton meskipun risol sebagai andalan m
asih muncul sebagai hidangan, tetapi terasa bila mereka mulai kehilangan kepercayaan diri. Saya yang dulunya betah berjam-jam bercengkerama dengan teman kini hanya sebatas tempat makan dan memilih nongkrong di tempat lain. Tempat ini sama seperti yang lainnya.
Apakah keramahan cafe di Malang mulai menghilang ditelan pasar persaingan yang mengedepankan ‘asal jadi cafe’?Lilin masih menyala ketika caesar salad dan s’mores pesanan tiba. Kawan saya mengusap mata, “Saya tidak bisa melihatmu dengan jelas. Orang-orang juga terlalu ramai. Tempat ini sedikit dipaksakan.” Saya menyetujuinya. Sajian yang dihidangkan sangat lezat dan kami berbicara sedikit mengenai makanannya karena satu hal yang kami sepakati: sebesar apapun cafe yang kami datangi ini, tetap saja tampak sesak karena kursi yang terlalu lebar dan pencahayaan yang kurang. Meja makan yang didesain untuk menampung banyak orang sekaligus memperlebar jarak kami berdua sehingga mengurangi intensitas dialog dan tentu saja gagal untuk membangun kedekatan yang seharusnya dapat difasilitasi oleh cafe ini. Rasanya seperti hanya menumpang makan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa tulisan ini mungkin berdasarkan personal taste ataupun raw experience, tetapi saya yakin beberapa dari Anda akan mengamini hal ini. Kini orang datang ke cafe hanya untuk sekedar ‘hadir’ seolah setiap cafe baru yang berdiri membeberkan daftar presensi bagi kalangan muda yang ingin mencari eksistensi. Namun polanya akan tetap sama: datang-makan-bayar-pulang. Mungkin bisa juga berubah menjadi datang-makan-check in-selfie-bayar-pulang. Sedikit cafetaria yang menyediakan ruang bagi pelanggannya untuk merasa nyaman dan diterima sebagai keluarga. Sebuah rumah yang selalu diingat tatkala pulang dari perantauan ataupun merasa suntuk dalam lingkungan yang stagnan.
Sebuah cafe yang ketika pelanggannya pulang, hanya agar mereka bisa merasakan gembiranya tiba kembali di rumah kedua.
Secangkir kopi hitam mengepulkan asap di atas meja. Sesosok bayangan terpantul di permukaannya yang beriak. Tawa dan canda seolah meresonansikan keramahan kota Malang. Kota yang mengawali perubahan makna kosakata dan mengayomi pemuda-pemudinya serta tempat bertukar pendapat dalam dialektika yang manis, semanis kraker gandum yang disantap bersama pahitnya kopi sebagai citarasa yang khas akan suasana nongkrong. Akankah kota Malang mampu menelurkan sangkar baru bagi muda-mudi yang ingin menyendiri maupun berbagi kebahagiaan? Langit senja pun hanya bisa mengangguk sendu menanti dinamika gaya hidup yang terus berulah di bawah temaram lampu perkotaan.
Disclaimer: Foto yang terpasang tidak mencerminkan cerita. Semua murni demi kepentingan stock foto saja.













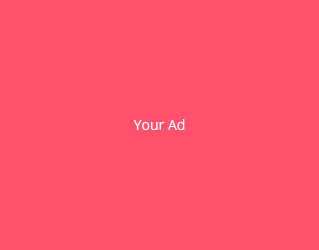

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih telah berkunjung. Sila untuk bertandang kembali bilamana saya membalas :)